Pengertian Paradigma Komunikasi
Sifat eklektif ini
telah dilukiskan oleh Wilburn Scramm sebagai jalan simpang yang
paling ramai dengan segala disiplin yang melintasinya. Sejak semula
para pakar acapkali mengkaji komunikasi manusia dengan menggunakan
konsep, teori dan model ilmu fisika, psikologi dan sosiologi, sejarah,
bahasa, dan sebagainya.
Tidak mengherankan bila hingga saat ini
masih banyak kalangan luar yang meragukan komunikasi sebagai
disiplin ilmu sendiri. Bahkan, beberapa kalangan psikolog atau sosiolog
yang masih merasa komunikasi manusia sebagai bagian dari
disiplinnya.
Kurang dipahami bahwa kajian komunikasi merupakan
bagian dari rumpun ilmu social yang lebih dulu ada, sehingga sangat
bersifat eklektif.
Dalam perkembangannya, sebagai suatu bidang kajian yang
eklektif, pengaruh disiplin lain terhadap ilmu komunikasi, terutama
ilmu fisika, psikologi dan sosiologi besar dan sangat terasa.
Hal ini
sekaligus telah melahirkan berbagai pendekatan dan wawasan yang
saling berbeda. Baik dalam merumuskan definisi komunikasi, penelitian
atau pengkajian empirik. Perbedaan-perbedaan itu pada akhirnya menumbuhkan dua hal yang sangat penting sebagai suatu fakta.
Yaitu
lahirnya fraksi-fraksi di kalangan ilmuwan komunikasi dan berbagai
paradigma atau perspektif dalam kajian komunikasi manusia.
Tak dapat disangkal bahwa para pakar ilmu komunikasi bukanlah
kelompok yang bersatu pandangan dan wawasan mengenai
konseptualisasi komunikasi sebagai suatu disiplin ilmiyah. Artinya para
pakar menghargai adanya perbedaan wawasan dan perbedaan paradigma
satu dengan lainnya.
Para pakar komunikasi merupakan kelompok yang
mempunyai ikatan yang sangat “longgar”, dan di dalamnya terdapat
fraksi-fraksi dengan paradigma yang beragam. Itulah sebabnya
Feyerabend menyebut komunikasi sebagai ilmu yang ditandai oleh
paradigma yang multiperspektif.
Multi paradigma seperti ini, tidak
hanya berlaku di disiplin komunikasi, karena hampir seluruh disiplin
dalam ilmu sosial, berparadigma ganda. Hal ini bukanlah sebuah
masalah tersendiri, tetapi sebaliknya, merupakan kekuatan ilmu sosial
yang membedakannya dengan ilmu alam.
Istilah paradigma berasal dari Thomas Kuhn (1970, 1974) yang di
gunakan tidak kurang dari 21 cara yang berbeda.
Namun Robert
Fredrichs (1970) berhasil merumuskan paradigma itu secara jelas
sebagai suatu pandanagn mendasar dari suatu disiplin ilmu teantang
apa yang menjadi pokok persoalan (subyek matter) yang semestinya
dipelajari.
Kuhn melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bukanlah terjadi secara kumulatif, tetapi terjadi secara revolutif. Dalam
masa tertentu ilmu sosial didominasi oleh suatu paradigma. Kemudian
terjadi pergantian dari paradigma lama yang memudar pada paradigma
baru.
Dalam hal ini, paradigma baru bukanlah kelanjutan dari
paradigma lama. Sosiologi misalnya, dalam perkembangannya memiliki
tiga paradigma yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu paradigma (1)
fakta sosial, (2) definisi sosial dan (3) perilaku sosial.
Ditempat berbeda Guba menjelaskan paradigma sebagai “…a set of
basic belief (or metaphysic) that diels with ultimits or first principle …a
world view that defines, for its holder, at the nature of the world. Oleh
karena itu paradigma berperan vital dalam melihat setiap kajian atau
penelitian. Sebab hal ini berkaitan dengan aspek filosofis dalam melihat
kompleksitas fenomena.
Dilihat dari beberapa paradigma yang selama ini berkembang AS.
Hikam menjelaskan perjalanan paradigma dibagi menjadi tiga bagian;
pertama, Paradigma Positivisme-empiris oleh beberapa orang dipandang
sebagai jembatan antara manusia dengan obyek diluar dirinya.
Salah satu
ciri dari paradigma ini adalah pemisahan antara pemikiran dengan
realitas.
Kedua adalah paradigma Konstruktivisme. Paradigma ini banyak
dipengaruhi oleh pandangan fenomenologi. Aliran ini menolak
pandangan empirisme yang memisahkan subyek dan obyek bahasa.
Dalam beberapa pandangan, paradigma ini tidak hanya dilihat sebagai
alat untuk memahami realitas obyektif belaka, dan yang dipisahkan dari
subyek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subyek sebagi faktor sentral dalam kegiatan wacana serta
hubungan-hubungan sosialnya.
Ketiga adalah Paradigma Kritis. Paradigma ini hanya sebatas
memenuhi kekurangan yang ada dalam paradigma konstruktivisme yang
dipadang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna.
Seperti ditulis AS.
Hikam paradigma Konstruktivisme masih belum
menganalisa faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam
setiap wacana yang pada gilirannya berperan sebagai pembentuk jenisjenis subyek tertentu berikut perilaku-perilakunya.
Paradigma ini
bersumber pada pemikiran Frankfurt School, yang berusaha mengkritisi
pandangan konstruktivis. Ia bersumber dari gagasan Marx dan Hegel
jauh sebelum sekolah Frankfurt berdiri.
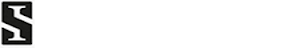


Posting Komentar untuk "Pengertian Paradigma Komunikasi"