Zaman Demokrasi Pancasila (1965−1998)
Salah satu tindakan MPRS ialah mencabut kembali Ketetapan No III/1963 tentang penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Tindakan lain yang dilakukan oleh Orde Baru adalah pembubaran PKI melalui TAP MPRS No. XXV/1966, sedangkan Partindo yang telah menjalin hubungan erat dengan PKI, dibekukan pada tahun yang sama.
Sementara itu terjadi perdebatan melalui berbagai seminar dan media massa, antara lain mengenai perlunya mendirikan demokrasi dan membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan merombak struktur politik yang ada.
Partai politik yang menjadi sasaran utama dari kecaman masyarakat dianggap telah bertindak memecah belah karena terlalu mementingkan ideologi serta kepentingan masing-masing. Keterlibatan ini sedemikian dalamnya sehingga mereka tidak sampai menyusun program kerja yang dapat dilaksanakan.
Salah satu instansi yang pada masa itu menarik perhatian adalah Seskoad, Bandung, lembaga yang sedikit banyak bertindak sebagai pusat pemikir (think tank) untuk Orde Baru. Salah satu peristiwa yang penting adalah diadakannya Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada tahun 1966.
Beberapa perwira ABRI dan beberapa tokoh sipil diundang untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut penegakan Orde Baru. Beberapa cendekiawan dari kalangan universitas diundang untuk memberikan makalah dan berpartisipasi dalam diskusi.
Salah satu makalah yang berjudul Pemilihan Umum dan Orde Baru membahas tentang dua sistem pemilihan, yaitu sistem perwakilan berimbang (atau sistem proporsional) dan sistem distrik yang umumnya belum dikenal di Indonesia.
Salah satu negara yang memakai sistem pertama adalah Nederland, sedangkan negara-negara AngloSaxon seperti Inggris dan Amerika memakai sistem kedua.
Mengingat keadaan di Indonesia, seandainya sistem distrik diselenggarakan di Indonesia sebagai pengganti sistem proporsional yang telah dipakai dalam Pemilihan Umum 1955, ada kemungkinan terjadinya penyederhanaan partai secara alamiah (artinya tanpa paksaan) karena jumlah partai kecil mungkin akan berkurang, sekurang-kurangnya mereka akan terdorong untuk bekerja sama satu sama lain.
Hal ini diharapkan dapat sedikit banyak meningkatkan stabilitas politik yang kadarnya pada masa itu masih lemah.50 Sebagai hasil perdebatan, baik dalam Seminar Angkatan Darat maupun di luar, akhirnya sistem distrik dituang dalam rancangan undang-undang pemilihan umum yang diajukan kepada parlemen pada awal tahun 1967 bersama dua RUU lainnya.
Akan tetapi ternyata rancangan-rancangan undang-undang ini sangat dikecam oleh partai-partai politik, tidak hanya karena dianggap dapat merugikan mereka, akan tetapi juga karena mencakup beberapa ide baru, seperti duduknya wakil ABRI sebagai anggota parlemen.
Akhirnya pada tanggal 27 Juli 1967 pemerintah dan partai-partai mencapai suatu kompromi di mana kedua belah pihak memberi konsesi.
Pemerintah mengalah dengan menyetujui sistem pemilihan umum proporsional, tetapi dengan beberapa modiikasi antara lain tiap kabupaten akan dijamin sekurang-kurangnya satu kursi sehingga perwakilan dari daerah di luar Jawa akan seimbang dengan perwakilan dari Jawa.
Di pihak lain, partai-partai mengalah dengan diterimanya ketentuan bahwa 100 anggota parlemen dari jumlah total 460 akan diangkat dari golongan ABRI (75) dan non ABRI (25) dengan ketentuan bahwa golongan militer tidak akan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih.
Berdasarkan Konsesus itu pada tanggal 8 desember 1967 RUU diterima baik oleh parlemen dan pemilihan umum Orde Baru yang diikuti oleh sepuluh partai politik (termasuk Golkar) diselenggarakan pada tahun 1971.
Akan tetapi ada berbagai kelompok dalam masyarakat dan di kalangan militer yang sangat kecewa dengan Konsensus yang dicapai dalam tahun 1967 karena dianggap sebagai kekalahan bagi kekuatan-kekuatan yang ingin merombak struktur politik.
Kelompok-kelompok ini tidak sabar melihat lambannya pembaharuan (reforms). Salah satu kelompok yang vokal adalah beberapa kaum cendekiawan dan beberapa kalangan militer di Jawa Barat, terutama dari kalangan Divisi Siliwangi dan Kostrad.
Mereka merasa terusik melihat partai-partai bertindak atas dasar memenangkan ideologinya tanpa mengajukan suatu program konkret yang dapat dilaksanakan.
Diharapkan bahwa masalah ini dapat diselesaikan lewat pembubaran partai dan penyusunan suatu sistem dwi-partai di mana kedua partai berorientasi pada program pembangunan, dan hanya berbeda dalam persepsi mengenai cara untuk melaksanakan pembangunan itu.
Pemikiran yang sangat baru ini mendapat dukungan kuat dari panglima Divisi Siliwangi Jenderal Dharsono. Ketika pemikiran ini untuk pertama kali muncul di Jawa Barat, langsung mendapat sorotan yang tajam dalam diskusi dan media massa.
Karena itu diadakan modiikasi sehingga konsep dwipartai diubah menjadi konsep dwi-grup. Perubahan ini mencakup ketentuan bahwa partai politik yang ada tidak dibubarkan, akan tetapi dikelompokkan dalam dua grup.
Akan tetapi, sewaktu dicoba dilaksanakan di beberapa kabupaten di Jawa Barat pada tahun 1968 dan awal 1969, ternyata tindakan ini mengundang banyak kecaman dan menimbulkan keresahan.
Keresahan itu baru reda waktu usaha dan kegiatan ke arah terbentuknya dwi-grup dihentikan tahun itu juga, dan partai politik merasa yakin bahwa eksistensi mereka sudah aman kembali. Dengan demikian berakhirlah eksperimen dengan sistem dwi-partai dan dwi-grup.
Mengapa eksperimen dengan sistem dwi-partai gagal? Beberapa alasan dapat dikemukakan, pertama sistem ini sama sekali baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Tidak ada satu pun preseden dalam sejarah bangsa kita sehingga dianggap terlalu radikal.
Mungkin ide itu belum dipikirkan secara matang, apalagi langkah-langkah pelaksanaannya. Lagi pula rencana ini kurang dimasyarakatkan sebelum diselenggarakan di beberapa tempat di Indonesia.
Mungkin eksperimen dengan dwi-partai terpengaruh oleh pengalaman di beberapa negara Barat seperti Inggris dan Amerika yang telah berhasil menghasilkan tentu bersamaan dengan beberapa faktor lain stabilitas yang cukup mantap dan langgeng.
Akan tetapi mengenai tujuan negara dan cara untuk mencapainya, perubahan ini mungkin dianggap terlalu radikal dan mengalami banyak kesulitan serta tantangan sehingga pada tahun 1969 ditinggalkan sama sekali.
Dipandang dari sudut teori perlu kita simak analisis Robert Dahl bahwa, sekalipun sistem dwi-partai dalam beberapa negara seperti Inggris dan Amerika telah dianggap sangat memuaskan, akan tetapi dalam suasana lain misalnya di negara di mana konsensus nasional rendah kadarnya (low consensus country), sistem dwi-partai malahan dapat mempertajam suasana konlik antara dua kekuatan politik itu, karena tidak ada kekuatan yang netral, yang dapat menengahi dua kelompok yang bertikai itu.
Dalam keadaan semacam ini, sistem ini malahan dapat mengakibatkan instabilitas politik. Dalam hubungan ini Indonesia dapat dikategorikan sebagai low consensus country di mana tidak ada tempat untuk sistem dwi-partai.
Sementara itu peranan golongan militer bertambah kuat yang menimbulkan sebuah rezim otoriter. Usaha penyederhanaan partai dilanjutkan dengan cara yang sedikit banyak radikal.
Di muka sepuluh partai termasuk Golkar, Presiden Soeharto mengemukakan sarannya agar partai mengelompokkan diri untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa partai kehilangan identitas masing-masing atau dibubarkan sama sekali.
 |
| Tanda Gambar Pemilu 1977 |
Pengelompokan ini mencakup tiga kelompok, yaitu Golongan Nasional, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya.
Usaha ini, yang sebenarnya ingin dilaksanakan sebelum pemilihan umum 1971, ternyata tidak dapat dituntaskan pada waktunya dan pemilihan umum 1971 diadakan dengan sembilan partai politik dan Golkar.
Pengelompokan dalam tiga golongan baru terjadi pada tahun 1973. Empat partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti ) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selain dari itu, lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.
Dengan demikian mulai pemilihan umum 1977 hanya ada tiga orsospol, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Langkah berikutnya untuk menata sistem kepartaian adalah konsep Pancasila sebagai satu-satunya asas.
Hal itu merupakan pelaksanaan dari gagasan yang telah dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan sidang paripurna DPR 16 Agustus 1982. Maksudnya agar tidak terjadi lagi penyimpangan seperti masa lalu atau persaingan antara partai karena tiap partai cenderung menonjolkan dan memperjuangkan asas mereka masing-masing.
Dengan demikian proses penyederhanaan partai yang telah dimulai pada zaman Demokrasi Terpimpin, akhirnya terlaksana secara efektif pada zaman Demokrasi Pancasila dengan tiga partai yang berasas Pancasila.
Mulai dengan Pemilihan umum 1982 sampai dengan pemilihan umum 1987 Golkar selalu menunjukkan kenaikan.55 Hanya pada pemilihan umum 1992 Golkar mengalami kemunduran. Akan tetapi pada pemilihan umum 1997 Golkar menang besar-besaran.
Kemenangan-kemenangan ini antara lain disebabkan karena diberlakukannya massa mengambang serta intervensi aparatur negara secara berlebih-lebihan.
 |
| Hasil Pemilihan Umum Orde Baru 1977-1997 |
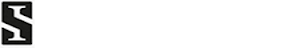
.jpeg)

Posting Komentar untuk "Zaman Demokrasi Pancasila (1965−1998)"