LANDASAN DAN TUJUAN POLITIK HUKUM
Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum.
Menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara.
Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan atau penidakberlakuan hukum.
Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (legal policy) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak berlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum.
Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan resultante (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.
Pencapaian tujuan negara harus senantiasa diusahakan terus menerus oleh penguasa yang sah sebagai terjemahan terselenggaranya fungsi-fungsi negara yang digariskan oleh UUD 1945, termasuk dalam kategori situasi darurat.
Dalam konteks pencapaian tujuan negara itulah, apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan warga negara dan integritas/ keutuhan wilayah, presiden diberikan wewenang untuk menetapkan suatau keadaan bahaya/darurat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 UUD 1945, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”
Penetapan adanya suatu keadaan bahaya/darurat oleh presiden dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah lanjutan yang sifatnya mampu mengatasi keadaaan yang dimaksud, termasuk melakukan pembatasan hak asasi manusia warga negara serta tindakan-tindakan pengecualian lainnya, dalam rangka penyelamatan negara, misalnya pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif seperti dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 ”Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.
Pelaksanaan kewenangan presiden untuk menyatakan adanya suatu keadaan bahaya adalah mutlak sebagai penjabaran dari fungsi kekuasaan pemerintahan, tidaklah ada otoritas lain yang memiliki kewenangan seperti halnya presiden untuk menggerakkan seluruh perangkat negara.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Willian B Fisch, yang menyatakan, “Strong presidents have claimed not only that the constitution provides ample authority to deal with emergencies as well as normal times, but the executive is the preeminent holder of the such authority.” (Asshiddiqie, 2010: 227).
Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tertinggi kekuasaan pemerintahan ketika dalam keadaan darurat memiliki perangkat untuk mengambil alih semua fungsi negara, dalam rangka menyelamatkan negara, termasuk melakukan pembatasan hak-hak warga negara serta menggerakan alat-alat opresif negara berdasarkan kondisi-kondisi objektif tertentu.
Dikemukakan oleh Emanuel Gross (2008), “In order to protect the public in times of emergency, the Executive Branch is conferred with wider administrative powers than in times of peace.” Jimly Asshiddiqie (2007:80) dalam pendapatnya tegas mengatakan, “Pejabat yang secara konstitusional berwenang untuk menetapkan dan mengatur keadaan darurat itu hanya presiden, bukan pejabat yang lain.”
Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran dari Rousseau, yang menyatakan bahwa kedaulatan—the souvereign memiliki ciri kesatuan, bersifat monistis, bulat dan tak terbagi, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat berubah.
Dalam praktiknya di dunia, terdapat banyak model penetapan keadaan darurat, sebagaimana diterapkan di sejumlah negara.
Model yang paling klasik, misalnya diterapkan pada masa kekuasaan Romawi dengan pendekatan kediktatoran (dictatorship); di Perancis dikenal dengan pendakatan state of siege, yang juga banyak diterapkan dalam negara yang menganut civil law system; sementara di Inggris menggunakan pendekatan martial law, yang banyak diadopsi oleh negara yang menganut common law system.
Merujuk pada pendapat Kim Lane Scheppele, dikatakan keadaan darurat adalah keadaan di mana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup-mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tindak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
Ditambahkannya, negara terpaksa melanggar prinsip-prinsip yang dianutnya sendiri dikarenakan adanya suatu ancaman yang serius, sehingga untuk menyelamatkan negara, tindakan penyimpangan tersebut terpaksa dilakukan.
Negara-negara di dunia juga beragam di dalam mengatur, memberikan pengertian dan kategorisasi mengenai keadaan darurat di dalam konstitusi nasionalnya.
Perbedaan ini umumnya didasarkan pada perbedaan antara berbagai kategori darurat dalam kondisi faktual tertentu, di mana pernyataan darurat tertentu dari beragam rezim darurat yang ada, secara konstitusional diperbolehkan.
Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi adanya perbedaan dalam metode deklarasi dan durasi waktu penerapan, tetapi juga hal-hal seperti sifat, ruang lingkup, dan lingkup kekuasaan darurat pemerintah, serta kemungkinan melenceng perlindungan hak konstitusional warga.
Beberapa konstitusi nasional sejumlah negara membuat struktur ganda dalam rezim darurat, seperti halnya yang dianut dalam konstitusi Belanda dan konstitusi Portugal, yang mengakomodasi adanya dua jenis keadaan darurat.
Konstitusi Belanda, misalnya membagi keadaan darurat menjadi “state of war” dan “state of emergency”. Sementara konstitusi Portugal membedakan antara “state of emergency” dengan “state siege”.
Dalam kasus-kasus adanya agresi dari pasukan asing maka negara akan dinyatakan dalam status “keadaan perang”, sedangkan apabila terdapat ancaman serius atau gangguan dari tatanan demokratis konstitusional atau bencana publik maka yang akan dikeluarkan adalah deklarasi “keadaan darurat.” Dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional juga diatur perihal “keadaan darurat.”
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ICCPR memaknai keadaan darurat sebagai “situasi yang mengancam terhadap kehidupan bangsa dan keberadaannya”.
Sementara General Comment Nomor 29 ICCPR, yang diadopsi pada 31 Agustus 2001 memaknai keadaan darurat sebagai “suatu keadaan yang luar biasa eksepsional dan bersifat temporer”.
Pengertian yang detail mengenai keadaan darurat dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dirumuskan di dalam prinsip-prinsip Siracusa tentang pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik.
Di dalam prinsip 39 dikatakan, bahwa keadaan darurat dideklarasikan apabila ada, “a threat to the life of the nation is one that: affects the whole of the population and either the whole or part of the territory of the State, and threatens the physical integrity of the population, the political independence or the territorial integrity of the State or the existence or basic functioning of institutions indispensable to ensure and protect the rights recognized in the Covenant.”
Penjelasan yang cukup detail mengenai keadaan darurat juga dikemukakan di dalam Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in A State of Emergency (Paris Standards), yang menjelaskan:
- The existence of a public emergency which threatens the life of the nation, and which is officially proclaimed, will justify the declaration of a state of emergency;
- The expression ‘‘public emergency” means an exceptional situation of crisis or public danger, actual or imminent, which affects the whole population or the whole population of the area to which the declaration applies and constitutes a threat to the organized life of the community of which the state is composed.”
Terkait dengan keadaan darurat, UUD 1945 memiliki struktur yang hampir serupa dengan konstitusi Belanda, yang menganut rezim ganda dalam keadaan darurat, yakni keadaan darurat perang serta keadaan bahaya.
Namun demikian, pasal 12 UUD 1945 tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai pengertian dan batasan keadaan bahaya atau keadaan darurat. Sementara bila merujuk pada penjelasan UUD 1945 praamandemen, dalam penjelasan pasal 12 dikatakan bahwa kekuasaan presiden dalam pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan residen sebagai kepala negara.
Merujuk pada pendapat Jimmly Asshiddiqie (2007: 59), keadaan bahaya atau keadaan darurat menurut UUD 1945 dapat dimaknai sebagai, suatu keadaan luar biasa atau di luar kebiasaan, di luar keadaan normal, ketika norma-norma hukum dan lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara tidak dapat berfungsi sebagaimana adanya menurut ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam keadaan normal.
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 UUD 1945 tersebut negara sudah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya, seperti halnya diatur dengan UU Nomor 23/PRP/1959 tentang keadaan bahaya, juga beberapa perundang-undangan lainnya.
Dalam praktik kenegaraan kekinian, khususnya yang berlangsung pasca-jatuhnya rezim militer Orde Baru, pendekatan di atas juga telah secara konsisten digunakan, seperti dalam pernyataan darurat sipil untuk wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sebagai upaya penyelesaian konflik sipil di wilayah tersebut, yang dideklarasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000, dan kemudian dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003.
Begitu pula dalam pernyataan keadaan darurat di Aceh, baik dalam tingkat darurat militer yang dideklarasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003, dan diturunkan statusnya menjadi darurat sipil melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004, serta kemudian dicabut dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005.
Dari berbagai uraian mengenai pengertian politik hukum di atas, dapat diambil hal yang bersifat substansi atau unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu
- Adanya produk hukum yang ditentukan;
- Adanya pihak atau organisasi yang berwenang;
- Adanya ketentuan atau asas tertentu; dan
- Untuk mencapai tujuan negara.
Produk hukum yang dimaksud dalam politik hukum adalah hukum positif (ius constitutum) yang dibuat dengan memperhatikan gejala-gejala sosial lainnya, khususnya gejala politik yang mempengaruhinya.
Produk hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat-pejabat administrasi negara yang oleh peraturan perundang-undangan atau oleh mandat dan atau delegasi dari penguasa yang berhak mengeluarkan produk hukum tersebut.
Selanjutnya, agar kebijakan (politik) penguasa dalam melahirkan suatu keputusan (beschekking) atau peraturan (regeling) yang merupakan bentuk riil hukum positif haruslah diuji dan diselaraskan dengan asas-asas hukum seperti asas untuk kepentingan umum agar nantinya dinyatakan absah dan bermanfaat tanpa melanggar hak-hak asasi rakyat.
Dari semuanya itu, hakikatnya dalam politik hukum hanyalah mengenai kebijakan penguasa dalam pembaharuan hukum positif yang mengarah pada tujuan negara agar dapat tercapai karena tujuan dari negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV mengandung suatu cita-cita luhur Bangsa Indonesia dalam mewujudkan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian rakyat Indonesia.
Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara.
Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusanrumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut.
Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya. Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum (rech politik) dan sosiologi hukumnya (rech sosiolgie).
Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.
Tahapan yuridis dan politis berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis menelurkan output peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap masyarakat.
Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.
Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia.
Artinya, baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses di atas.
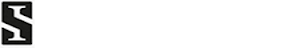


Posting Komentar untuk "LANDASAN DAN TUJUAN POLITIK HUKUM"