Prinsip Dasar Antropologi
Setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki prinsip-prinsip dan cara kerja secara ilmiah. Tahukah kalian apa prinsip dari ilmu antropologi? Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar antropolog. Simak penjelasan berikut!
1. Pendekatan Holistik dalam Antropologi
Sebagai ilmu yang mengkaji manusia dan kebudayaan, antropologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang bersifat holistik (Saifuddin, 2006). Antropologi bersifat holistik karena antropologi mengkaji pengalaman manusia secara menyeluruh.
Dalam arti, antropolog melihat keterkaitan antara faktor kehidupan manusia dan mempelajari hubungan di dalamnya. Para antropolog tertarik pada seluruh fenomena manusia dan pada bagaimana berbagai aspek kehidupan manusia berinteraksi.
Pendekatan holistik dapat dipahami sebagai cara berpikir bahwa suatu fenomena terhubung dengan fenomena lain dan menciptakan semacam entitas berdasarkan keterkaitan dan pengaruh timbal balik antara berbagai elemennya.
Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman utuh tentang fenomena sosial budaya dengan menggali dari berbagai aspek kehidupan manusia yang memengaruhinya. Seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami suatu kebudayaan dengan mempelajari hanya satu aspek saja dari sejarah, bahasa, tubuh, atau masyarakat kita yang kompleks.
Dengan menggunakan pendekatan holistik, para antropolog mengungkap kompleksitas fenomena biologis, sosial, atau budaya. Ringkasnya, pendekatan holistik memeriksa bagaimana berbagai aspek kehidupan manusia saling memengaruhi (Brown et al., 2020).
Pendekatan holistik merupakan bagian sentral dalam perspektif antropologi (Otto & Bubandt, 2010). Pendekatan holistik merupakan karakteristik khas dari ilmu antropologi, yang membedakan antropologi dengan disiplin ilmu lain.
Disiplin ilmu lainnya hanya berfokus pada satu faktor-biologi, psikologi, fisiologi, atau masyarakat dalam menjelaskan perilaku manusia (Otto & Bubandt, 2010).
Pemahaman holistik sebagai pendekatan komprehensif terhadap kondisi manusia ini berkaitan erat dengan pandangan antropolog Amerika tentang antropologi yang terdiri dari empat sub-bidang, di antaranya antropologi budaya, antropologi fisik, linguistik, dan arkeologi, yang secara bersamasama membentuk pemahaman menyeluruh tentang kemanusiaan (Brown et al., 2020; Otto & Bubandt, 2010).
Sementara antropolog sering memfokuskan kajian pada satu sub-bidang antropologi yang spesifik, penelitian spesifik mereka berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang kondisi manusia, yang terdiri dari budaya, bahasa, adaptasi biologis dan sosial, serta asal usul dan evolusi manusia (Brown et al., 2020).
Pendekatan holistik berkaitan erat dengan teknik observasi partisipan. Observasi partisipan sendiri merupakan teknik melakukan penelitian atau praktik kerja lapangan etnografi di mana para antropolog tinggal bersama dan mengambil bagian dalam kehidupan informan mereka untuk mendapatkan data hasil pengamatan yang lebih baik.
Dengan melakukan observasi partisipan, para antropolog lebih mampu melihat integrasi antara bidang kehidupan yang dipandang terpisah dalam masyarakat yang lebih kompleks (seperti, kaitan antara kekerabatan, agama, politik, dan ekonomi).
Observasi partisipan juga memampukan kita melihat lingkup atau bidang yang terpisah sebagai bagian dari keseluruhan sosial, sehingga mampu menerapkan pendekatan holistik (Otto & Bubandt, 2010). Ringkasnya, observasi partisipan menjadi kunci dalam pendekatan holistik untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena sosial budaya secara menyeluruh.
2. Perspektif Emik dan Etik
Masyarakat seringkali memahami suatu kebudayaan dari kaca mata kebudayaannya sendiri dalam menggambarkan dan mengkaji kebudayaan lain. Hal itu juga menimpa para antropolog.
Para antropolog dihadapkan pada dilema apakah berangkat dari perspektif kebudayaan masyarakat yang diteliti atau mewakili cara pandangnya sebagai ilmuan.
Dalam disiplin ilmu antropologi, kedua hal yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan melukiskan suatu kebudayaan tersebut disebut dengan perspektif emik dan etik.
Perspektif ini mengemuka sekira awal abad ke-20, di mana para antropolog kemudian berupaya menerapkan pembedaan perspektif etik dan emik (ethic and emic distinction) untuk mengatasi masalah tersebut (Saifuddin, 2006).
Istilah emik dan etik sebetulnya meminjam konsep kajian antropologi linguistik yaitu pembedaan kata “fonemik” dan “fonetik”.
Emik dan etik merupakan dua sudut pandang atau perspektif dasar dari mana seorang pengamat dapat menggambarkan perilaku manusia atau kebudayaan (Ethnology-Encyclopedia, 1996b; Mostowlansky & Rota, n.d.). Dengan menggunakan istilah tersebut, antropologi membedakan perspektif emik dan etik sebagai berikut:
a. Emik
Istilah emik berasal dari istilah linguistik, yaitu ‘fonemik’ (phonemic). Secara sederhana, emik mengacu pada sudut pandang masyarakat yang diteliti atau native’s point of view (Saifuddin, 2006).
Emik dapat dipahami sebagai cara untuk memahami dan melukiskan suatu kebudayaan dengan mengacu pada sudut pandang atau perspektif masyarakat pemilik kebudayaan yang dikaji.
Apabila mengkaji suatu kebudayaan menggunakan perspektif emik, temuan yang dihasilkan akan bersifat khas-budaya (culture-specific) atau akan menghasilkan temuan yang berbeda pada konteks budaya yang berbeda.
Menurut Marvin Harris (dalam Saifuddin, 2006), kerja emik dianggap mencapai tingkat tertinggi ketika antropolog melibatkan masyarakat pelaku kebudayaan dalam analisis yang dilakukan oleh pengamat (observer).
Analisis secara emik dianggap berhasil apabila suatu kajian mengenai kebudayaan mampu mengungkap pernyataan-pernyataan yang mewakili cara pandang native atau warga setempat sebagai suatu hal yang nyata, bermakna dan sesuai dengan persepsi masyarakat yang diteliti mengenai kebudayaan mereka.
Hal ini berarti harus terdapat konsensus atau kesepakatan bersama antara para informan asli, yang setuju bahwa deskripsi emik tersebut telah sesuai dengan persepsi bersama yang menjadi karakteristik budaya mereka.
Pengetahuan emik dapat diperoleh baik melalui wawancara maupun observasi, karena ada kemungkinan pengamat yang objektif dapat menarik kesimpulan dari persepsi masyarakat yang diteliti (Ethnology-Encyclopedia, 1996b).
Fenomena budaya atau perilaku manusia yang dianggap sebagai suatu kebenaran, belum tentu merupakan suatu hal yang dianggap benar oleh masyarakat dari budaya lain di luar kita.
Sebagai contoh kebiasaan tersenyum kepada orang asing yang ditemui di jalan merupakan suatu hal yang menjadi pertanda keramahan dan kesopanan terhadap seseorang.
Namun, bagi warga Rusia, tersenyum kepada orang asing merupakan suatu hal yang aneh, karena senyum merupakan pertanda ketertarikan terhadap seseorang.
Selain itu, di Indonesia kebiasaan membunyikan klakson mobil atau motor merupakan cara untuk menyapa orang yang dikenal pada saat berpapasan di jalan. Namun, di Norwegia, membunyikan klakson mobil dianggap sebagai hal yang sensitif dan menjadi pertanda suatu kondisi darurat.
Berdasarkan contoh di atas, dapat kita ketahui bahwa suatu fenomena budaya pada suatu tempat belum tentu memiliki nilai, pemahaman, dan berlaku sama di tempat lain. Dengan demikian perspektif emik diperlukan untuk dapat mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis suatu kebudayaan dari sudut pandang pelaku kebudayaan itu sendiri.
Salah satu implikasi dari perspektif emik dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Malinowski dalam menggambarkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat Pulau Trobriand melalui sudut pandang masyarakat itu sendiri.
Dalam mempelajari menggambarkan kebudayaan masyarakat Kepulauan Trobriand. Malinowski menetap dan tinggal bersama suku pribumi Trobriand kurang lebih selama 4 tahun (1915 sampai 1918).
Malinowski dapat menguasai bahasa asli setempat, menjalin persahabatan dengan penduduk setempat, sehingga dapat melukiskan secara rinci budaya Kula atau adat tukar-menukar hadiah yang dilakukan oleh suku Trobriand dengan suku bangsa lain yang tinggal di pulau terdekat.
Dalam memahami menjelaskan budaya Kula, dan menganalisis tata sosial suku Trobriand, Malinowski menerapkan perspektif emik. Malinowski berusaha untuk memahami kebudayaan dari sudut pandang masyarakat yang diteliti dengan mempelajari bahasa asli.
Penguasaan bahasa asli memudahkan Malinowski memaknai ucapan dan interaksi verbal sesuai bahasa yang digunakan oleh suku Trobriand. Kemudian, Malinowski menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh dunia luar suku Trobriand sebagaimana tertuang dalam karyanya Argonauts of the Western Pacific.
b. Etik
Istilah etik dalam antropologi berasal dari istilah fonetik (phonetic) pada ilmu linguistik. Etik merupakan pendekatan atau cara untuk memahami dan melukiskan suatu kebudayaan dengan mengacu pada sudut pandang peneliti (scientist’s point of view).
Cara pandang etik merupakan penjelasan, deskripsi dan analisis yang mewakili cara pandang pengamat sendiri sebagai orang di luar masyarakat yang ditelitinya.
Apabila mengkaji suatu kebudayaan secara etik, temuan yang dihasilkan cenderung sama pada berbagai konteks budaya, atau lebih bersifat universal. Deskripsi atau penjelasan antropologis dianggap sebagai cara pandang etik, apabila dapat diterapkan secara lintas budaya.
Deskripsi atau pengetahuan etik tidak bergantung pada acuan khusus, atau bersifat lokal semata, melainkan harus dapat digeneralisasi.
Selain itu, deskripsi oleh pengamat dapat dilakukan secara independen, artinya deskripsi etik harus dapat dikembangkan oleh pengamat bebas atau independent observer dengan memperoleh hasil yang sama ketika validasi dilakukan.
Pendekatan etik dan emik telah diposisikan sebagai metode penelitian yang berbeda satu sama lain. Metode penelitian dengan pendekatan atau perspektif emik lebih cenderung melibatkan pengamat secara berkelanjutan di mana peneliti membenamkan dirinya dalam masyarakat yang ditelitinya, mengembangkan hubungan dengan informan, dan mengambil peran sosial dalam menyikapi kebudayaan masyarakat yang ditelitinya.
Deskripsi emik juga dapat dilakukan dalam program wawancara dan observasi yang lebih terstruktur. Sedangkan, metode penelitian dengan pendekatan etik lebih cenderung melibatkan pengamatan singkat dan terstruktur dari beberapa kelompok budaya, dalam arti pengamatan dilakukan secara paralel pada pengaturan atau setting sosial yang berbeda (Morris et al., 1999).
Namun, tidak semua peneliti antropologi berpendapat bahwa pendekatan emik dan etik harus dipisahkan. Beberapa telah menyarankan bahwa peneliti harus memilih pendekatan yang bergantung pada jenis dan misi penelitian.
Sebagai contoh, pendekatan emik berfungsi paling baik dalam penelitian eksplorasi, sedangkan pendekatan etik berfungsi paling baik dalam menguji hipotesis (Morris et al., 1999). Dalam perkembangannya, konsep emik dan etik menjadi topik perhatian di kalangan antropolog, karena berkaitan dengan cara memandang dan menggambarkan suatu kebudayaan.
Namun, pada akhirnya, sebagian besar antropolog setuju bahwa tujuan penelitian antropologi harus memperoleh pengetahuan emik dan etik. Pengetahuan emik sangat penting untuk pemahaman yang bersifat intuitif dan empatik mengenai suatu budaya, dan penting untuk melakukan penelitian etnografis yang efektif.
Lebih lanjut, pengetahuan emik sering menjadi sumber inspirasi bagi hipotesis etik. Pada sisi lain, pengetahuan etik sangat penting untuk perbandingan lintas budaya. Perspektif emik diperlukan untuk mengimbangi perspektif etik dalam memahami suatu fenomena budaya secara lebih menyeluruh. Sebagai contoh, gambar di atas menunjukkan adanya pemulung di kawasan pinggiran kota.
Orang lain memandang bahwa pemulung adalah orangorang yang mengambil barang bekas dan mengais rezeki dari sampahsampah bekas untuk kemudian dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akan tetapi, dari sudut pandang emik yaitu sudut pandang pemulung itu sendiri belum tentu sama. Bagi pemulung, tanpa adanya mereka dan kegiatan memulung yang dilakukan, petugas kebersihan akan kerepotan untuk membersihkan sampah di jalanan.
Terlebih lagi, bagi mereka, kegiatan tersebut ikut menyalurkan sampah anorganik yang masih dapat digunakan ke tempat yang tepat sekaligus mendatangkan penghasilan.
Dengan demikian, sudut pandang dari pemulung mengenai kegiatan memulung merupakan emik karena berasal dari pelaku budaya itu sendiri. Sedangkan sudut pandang masyarakat atau orang luar mengenai kegiatan memulung adalah cara pandang etik karena mengacu pada pandangan pengamat atau orang luar yang bukan pelaku budaya.
3. Relativisme Kebudayaan
Keberagaman dan perbedaan budaya dalam masyarakat dapat mendorong munculnya suatu sikap yang disebut dengan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sebuah sikap yang memandang bahwa budayanya sendiri lebih baik dibandingkan dengan budaya lain.
Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik sosial dalam masyarakat karena cenderung menggunakan standar nilai dari kebudayaannya sendiri untuk memandang kebudayaan orang lain.
Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu sikap dan pandangan yang dapat mengatasi tumbuhnya sikap tersebut, terutama dalam kajian antropologi menggambarkan kebudayaan masyarakat. Dalam ilmu antropologi budaya, terdapat istilah relativisme budaya yang menjadi salah satu prinsip antropologi.
Prinsip ini digunakan dalam melihat suatu nilai, perilaku, dan budaya yang ada dalam suatu kelompok masyarakat sesuai budaya masyarakat yang dikaji itu sendiri.
Relativisme budaya merupakan suatu pandangan bahwa setiap masyarakat, nilai, kebudayaan, kebiasaan, kepercayaan, dan aktivitas harus dipahami dari cara atau sudut pandang budaya itu sendiri (Erikson, 2004).
Prinsip ini diperkenalkan oleh antropolog Franz Boas, pada abad ke-20, yang mengemukakan gagasannya bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang absolut melainkan relatif. Namun, istilah relativisme budaya baru dikembangkan oleh murid-murid Boas yang pertama kali digunakan oleh Alain Cocke pada tahun 1924.
Dalam sejarah antropologi, prinsip relativisme kebudayaan ini mulai muncul sebagai reaksi terhadap evolusionisme budaya Darwin, August Comte, E.B. Tylor, Herbert Spencer, dan Lewis Henry Morgan serta gerakan nasionalisme Eropa akhir abad ke-19 dan ke-20 (Ethnology-Encyclopedia, 1996a).
Menurut pandangan evolusionis awal, umat manusia mengalami tingkat perkembangan dari kebiadaban atau barbarisme menuju peradaban yang lebih baik.
Namun, di sisi lain pelaku budaya yang mendeklarasikan bahwa budayanya sendiri telah mencapai puncak tertinggi dari proses perkembangan ini ternyata menyimpan doktrin nasionalis yang rasis, yang berlaku dalam dua perang dunia.
Nasionalisme yang rasis ini bahkan dimulai sejak abad ke-16 dan ke-17. Pada zaman penjelajahan Eropa, Renaisans atau Abad Pencerahan, mereka memahami orang non-Eropa berdasarkan cara mereka sendiri dan dalam konteks kehidupan mereka sendiri.
Perintis awal relativisme budaya, seperti Franz Boas (1911, 1940), muridnya Ruth Benedict (1934), Margaret Mead (1950), dan Melville Herskovits (1948) yang sangat teliti dalam sejarah, menolak doktrin superioritas-inferioritas budaya.
Menurut mereka, budaya harus dipelajari dengan istilah mereka sendiri sebagai satu keseluruhan yang terintegrasi.
Relativisme budaya memandang bahwa pada prinsipnya tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau baik (superior) maupun lebih buruk atau rendah (inferior) dibandingkan dengan kebudayaan yang lain, karena berkaitan dengan nilai budaya masing-masing.
Prinsip relativisme budaya menolak pandangan bahwa terdapat kebenaran atau nilai yang bersifat universal.
Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa suatu kelompok mungkin menerapkan nilai-nilai bersama yang berbeda karena keyakinan mereka tentang situasi mereka juga berbeda dari kelompok masyarakat lain (Wong, 2006).
Kebudayaan masyarakat yang beragam dan masing-masing memiliki cara yang berbeda dan unik dalam mengatur hubungan dan tindakan anggota masyarakatnya.
Setiap budaya memiliki sistem moral dan standar etikanya sendiri, sehingga sesuatu tindakan manusia atau nilai budaya yang dianggap benar pada suatu kelompok masyarakat, belum tentu dianggap baik dan benar oleh masyarakat lain.
Dengan demikian, dalam pandangan relativisme budaya, kebudayaan dipandang sebagai suatu yang bersifat relatif, parsial atau tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada konteks budaya masyarakat itu sendiri, yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain.
Semua konten budaya harus dipahami dan dijelaskan sesuai dengan konteks budaya di mana ia berada. Bentuk relativisme budaya ini memaksa peneliti untuk mencoba memahami dunia batin suatu kelompok yang memiliki nilai, kepercayaan, peran, ekonomi, struktur politik, bahasa, gerak tubuh, dan sejenisnya sangat berbeda dari pengamat (EthnologyEncyclopedia, 1996a).
Hal tersebut kemudian mensyaratkan seorang antropolog untuk mengembangkan empati, simpati, rasa menghormati serta menempatkan semua perilaku manusia dalam konteks bagaimana perilaku dibentuk atau dialami oleh orang atau kelompok lain.
Dorongan empatik kemudian menjadi bagian inti relativisme budaya (EthnologyEncyclopedia, 1996a). Relativisme pada dasarnya lebih mengacu pada suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi beragam budaya sebebas mungkin dari prasangka sosial peneliti.
Prinsip relativisme budaya dapat mengimbagi kecenderungan seseorang atau peneliti dalam menggunakan nilai dan kebudayaannya sendiri sebagai standar yang digunakan dalam memahami dan menilai kebudayaan lain.
Dengan demikian, antropolog dapat memperoleh pemahaman mengenai suatu kebudayaan dari sudut pandang dan pengetahuan dari kebudayaan itu sendiri (Henslin, 2006). Relativisme bertujuan untuk belajar melihat dunia sejauh mungkin dengan cara yang sama seperti informan atau pelaku kebudayaan melihat budaya mereka sendiri (Erikson, 2004).
Relativisme budaya tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga prasangka peneliti, tetapi juga untuk mengembangkan sikap jujur dalam menggambarkan beragam budaya.
Prinsip relativisme kebudayaan dapat digunakan dalam kajian antropologi terhadap unsur-unsur suatu kebudayaan, untuk memperoleh pemahaman yang baik tanpa harus memberikan penilaian bahwa unsur budaya tersebut lebih baik atau lebih buruk berdasarkan budaya dari pengamat sendiri (Henslin, 2006).
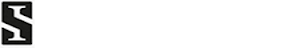



Posting Komentar untuk "Prinsip Dasar Antropologi"